
JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) menyelenggarakan Seri Seminar Agraria, Pangan, dan Pertanian Menuju Konferensi Internasional Reforma Agraria dan Pembangunan Pedesaan (ICARRD+20) “Pemenuhan Hak Atas Tanah” pada Kamis (06/11/2025) di Sofyan Hotel Cut Meutia, Menteng, Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan keterlibatan Indonesia pada Konferensi Internasional Reforma Agraria dan Pembangunan Pedesaan (ICARRD+20) yang akan berlangsung di Cartagena, Kolombia, pada Februari 2026 mendatang.
Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kalangan, mulai dari kementerian, lembaga internasional, organisasi tani dan nelayan, hingga akademisi. Hadir di antaranya Kepala Perwakilan FAO Indonesia, Rajendra Aryal, yang menyampaikan keynote speech melalui video; Zainal Arifin Fuat selaku Koordinator Internasional La Via Campesina Asia Tenggara dan Asia Timur sekaligus Wakil Ketua Umum SPI; Samsul Widodo, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDT RI; Rudi Rubijaya, Direktur Land Reform Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN RI; serta Asmarhansyah, Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian merangkap Plt. Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Pertanian Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI. Dari sisi gerakan rakyat dan akademisi, turut hadir Sugeng, Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), serta Bayu Eka Yulian, Kepala Pusat Studi Agraria IPB.

Seminar dibuka secara resmi oleh Ketua Umum SPI, Henry Saragih. Dalam sambutannya, Henry menegaskan bahwa “agenda reforma agraria adalah agenda internasional yang dihidupkan kembali pada 1976 di Roma, karena kolonialisasi telah meninggalkan ketimpangan yang begitu serius.” Ia menekankan distribusi tanah kepada petani merupakan langkah penting untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan yang masih terjadi sampai sekarang ini.
Henry juga mengingatkan pentingnya memperkuat hak-hak petani di tengah tantangan kebijakan nasional. Ia menegaskan bahwa secara hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar yang kuat untuk melindungi petani, mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria hingga UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tahun 2013. Namun, lahirnya kebijakan seperti UU Cipta Kerja justru dianggap melemahkan capaian tersebut. “Kita sudah punya instrumen hukum di tingkat nasional dan internasional seperti UNDROP, tapi persoalannya adalah bagaimana memastikan hak-hak itu benar-benar dijalankan,” ujarnya.

Rajendra Aryal menyampaikan bahwa Reforma agraria yang efektif adalah instrumen penting untuk memperkuat produksi pertanian memastikan stabilitas sosial dan mencapai Sustainaible Development Goals (SDGs) terutama SDGs 1 (tidak ada kemiskinan) dan SDGs 2 (nol kelaparan). “
FAO secara terus menerus dan secara aktif mendukung upaya reforma agraria secara global menekankan tata kelola lahan yang bertanggung jawab, mengamankan hak kepemilikan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan sebagai pusat pencapaian ketahanan pangan dan pembangunan perdesaan,” ujarnya dalam keynote speech yang disampaikanya dalam seminar. Rajendra juga menegaskan pentingnya evaluasi penerapan VGGT sebagai salah satu capaian utama ICARRD 2006, guna memperkuat komitmen global menuju reforma agraria yang adil dan berkelanjutan menjelang ICARRD+20.

Zainal Arifin Fuat menyampaikan bahwa banyaknya persoalan lahan, kriminalisasi terhadap petani, dan dampak perubahan iklim menunjukkan perlunya konferensi ICARRD digelar kembali setelah 20 tahun. Ia juga memaparkan perkembangan menuju konferensi ICARRD+20 yang mana 101 negara sudah positif hadir pada konferensi itu. “Semoga Indonesia menjadi salah satu dari negara itu, sebagai bentuk komitmen pelaksanaan reforma agraria di negara ini,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa meningkatnya angka kelaparan dunia saat ini tidak terlepas dari lima faktor utama sebagaimana dilaporkan dalam The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2025. Di antaranya adalah dampak pandemi Covid-19, perubahan iklim ekstrem, konflik sosial, ketidakstabilan ekonomi global, serta penguasaan korporasi besar terhadap sistem pangan dunia. Faktor terakhir ini disebut sebagai yang paling menentukan, karena segelintir perusahaan menguasai rantai pangan dari hulu hingga hilir, membuat akses masyarakat terhadap pangan semakin terbatas.

Dari sisi pemerintah, para narasumber menyoroti pentingnya memperkuat kembali hubungan antara reforma agraria, pembangunan desa, dan ketahanan pangan nasional. Samsul Widodo menekankan perlunya membenahi sistem ekonomi dan perdagangan di tingkat desa agar tidak terus terserap oleh arus ekonomi perkotaan. Ia menyoroti ketimpangan distribusi hasil pertanian, lemahnya kelembagaan ekonomi desa, serta dominasi produk pangan instan yang menggeser pangan lokal, sebuah fenomena yang disebutnya sebagai bentuk gastrokolonialisme. Topik ini sangat relevan untuk dibahas di ICARRD+20 nantinya, sehingga desa tidak terperangkap dengan gastrokolonialisme.

Sementara itu, Rudi Rubijaya menuturkan di Indonesia reforma agraria dimaknai dalam dua hal, yakni penataan aset dan penataan akses. Dalam konteks penataan aset dilakukan dengan cara legalisasi aset dan redistribusi tanah. Kemudian penataan akses berbicara tentang pemetaan sosial, pendampingan usaha dengan pembentukan kelompok atau badan usaha, serta penggunaan teknologi tepat guna dalam berwawasan lingkungan. Ia menambahkan beberapa usulan yang akan dibawa ke ICARRD+20, antara lain penyelesaian konflik tenurial; penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; penataan aset, baik melalui fresh land maupun penguatan hak atas tanah; penataan akses untuk emamstikan kesejahteraan; dan penataan lingkungan permukiman yang sehan dan terjangkau.

Asmarhansyah berbicara mewakili Kementerian Pertanian RI menekankan pada penyiapan pangan untuk ke depannya dalam mengantisipasi atau mengatasi angka populasi di dunia yang terus meningkat. Selain itu, pemerintah juga berfokus dalam mewujudkan swasembada pangan. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah melakukan program program cetak sawah yang mana ini menjadi target reforma agraria. Hal ini juga menjadi usulan untuk ICARRD+20 2026 mendatang.
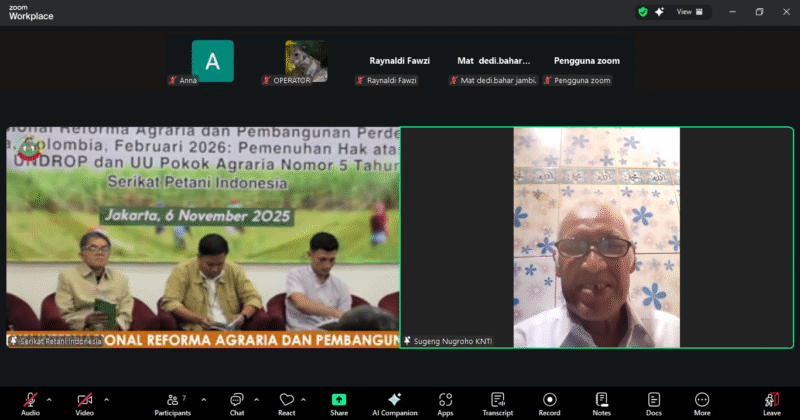
Sugeng, yang hadir secara daring, menyoroti bahwa hingga kini reforma agraria belum sepenuhnya berpihak pada rakyat kecil. Menurutnya, ketimpangan penguasaan sumber daya masih kuat, terutama di wilayah pesisir. “Nelayan berkonflik dengan korporasi dan kapal-kapal besar. Ini menunjukkan bahwa agraria masih dikuasai oleh pemilik modal, bukan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan dua pilar reforma agraria yang tak bisa dipisahkan dalam konteks Indonesia, sehingga kebijakan agraria ke depan harus mencakup darat dan laut secara adil dan berkelanjutan.

Bayu Eka Yulian, dari perspektif akademisi, memaparkan lima poin penting yang perlu dibawa sebagai bekal menuju konferensi ICARRD+20. Pertama, indeks kinerja pansus penyelesaian reforma agraria tidak hanya diukur secara kuantitatif, tetapi juga harus memiliki indikator kualitatif. Kedua, arsitektur kelembagaan reforma agraria perlu diperkuat dengan memastikan Badan Percepatan Reforma Agraria diisi oleh unsur masyarakat sipil, bukan semata pejabat negara. Ketiga, penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan dalam agenda reforma agraria. Keempat, perlu evaluasi menyeluruh terhadap TORA dan subjek reforma agraria secara partisipatif dan demokratis. Kelima, diperlukan orkestrasi kelembagaan yang lebih kuat dalam pelaksanaan access reform agar ada keberlanjutan setelah reforma agraria dilakukan.
Melalui seminar ini, SPI menegaskan perlunya agenda bersama antara pemerintah dan gerakan rakyat untuk memperkuat pelaksanaan reforma agraria, serta merevisi kebijakan yang tidak sejalan dengan kedaulatan pangan. Momentum ini juga menjadi langkah penting untuk menyusun rekomendasi dan pandangan bersama yang akan dibawa ke konferensi ICARRD+20 di Kolombia tahun 2026 mendatang, sebagai kontribusi Indonesia dalam mendorong terwujudnya reforma agraria sejati dan sistem pangan yang berdaulat di tingkat global.